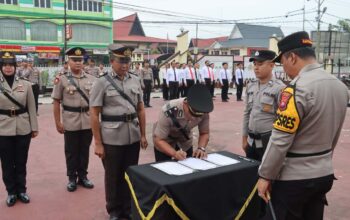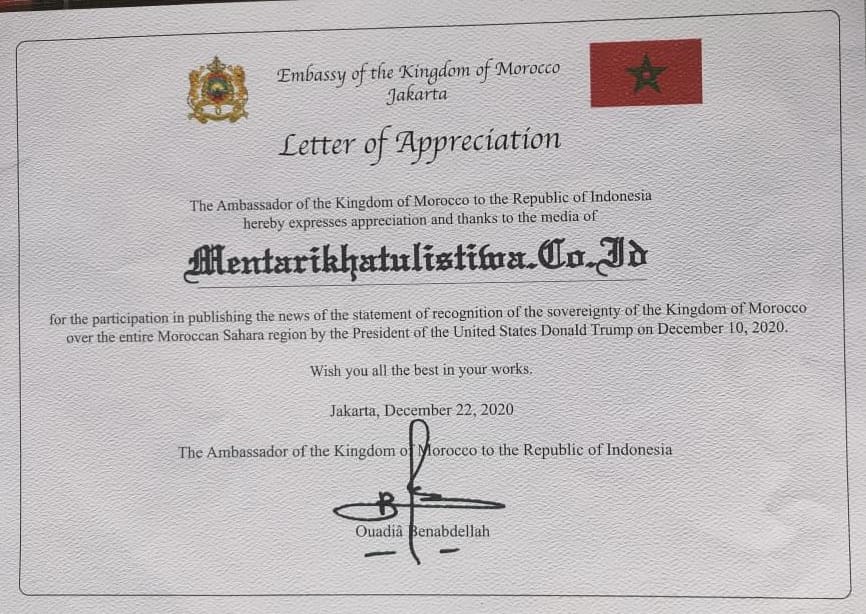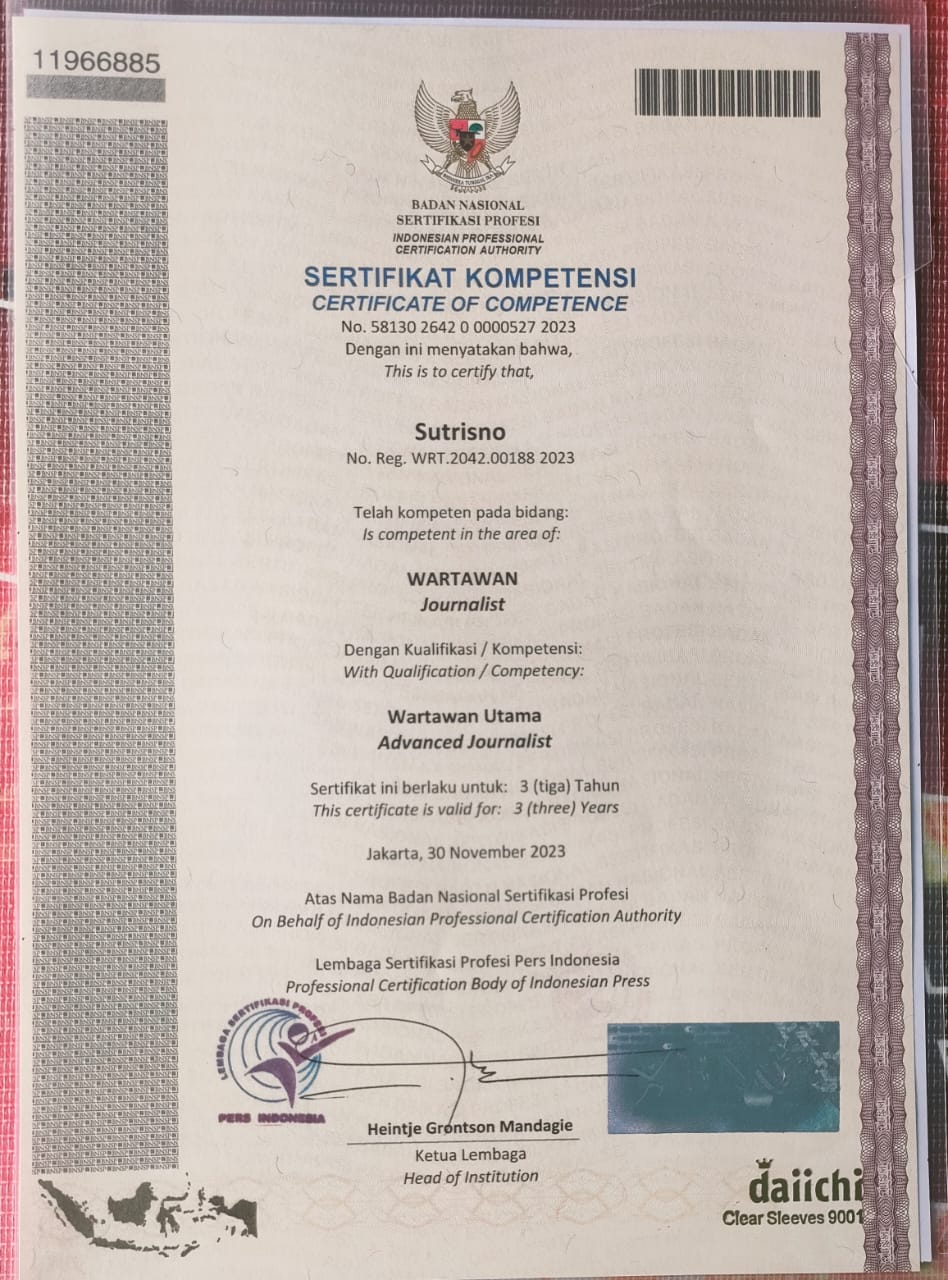Pekanbaru,mentarikhatulistiwa.co.id – Perkara Nomor 1357/Pid.B/2025/PN Pbr yang menyidangkan kasus kriminalisasi aktivis Jekson Sihombing di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 10 Februari 2026 menjadi sorotan publik. Pasalnya dalam sidang tersebut, enam Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Riau mangkir alias tidak hadir tanpa alasan sah dan tanpa penunjukan pengganti.
Ketidakhadiran ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum acara pidana, asas fair trial, dan hak terdakwa atas peradilan cepat. Nama-nama JPU yang absen dan harus diusut adalah Rama Eka Darman, Marthyn Luther, Edy Prabudy, Mutiara Sandhy Putri, Muhammad Habibi, dan Edhie Juniadi Zarly. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Jonson Parancis sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Harsoyo dan Refi Damayanti sebagai Hakim Anggota, diminta untuk menegur keras para JPU yang melanggar hukum ini.
Berdasarkan resume hasil persidangan pada Selasa, 10 Februari 2026, kemarin, penasehat hukum Jekson Sihombing, Advokat Padil Saputra, S.H., M.H., menyampaikan kekecewaannya atas sikap dan perilaku JPU yang dinilainya tidak professional dan melecehkan pengadilan. Wilson Lalengke, tokoh HAM internasional Indonesia yang mengawal kasus ini bahkan mengecam keras tingkah laku para jaksa tersebut dengan mengatakan bahwa para JPU itu sebagai pengkhianat hukum dan keadilan.
“Tinggkah-pola JPU yang mangkir dari persidangan adalah pengkhianatan terhadap hukum dan keadilan, mereka secara brutal merampas hak Jekson Sihombing sebagai warga negara atas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya murah,” tegas Wilson Lalengke mengungkapkan kekecewaannya, Rabu, 11 Februari 2026, sambil menekankan agar pimpinan Kejaksaan Agung mengambil tindakan tegas terhadap para jaksa yang tidak professional dan makan gaji buta itu.
Pelanggaran Hukum yang Terjadi
Merujuk pada UU Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, ketidakhadiran JPU bertentangan dan melanggar sejumlah pasal dalam KUHAP ini. Pertama, Pasal 201 KUHAP baru mewajibkan kehadiran Penuntut Umum pada hari sidang. Kedua, Pasal 65 dalam KUHAP yang sama menegaskan fungsi penuntutan mencakup kewajiban aktif hadir di persidangan. Ketiga, Pasal 252 KUHAP baru mewajibkan penunjukan pengganti jika JPU berhalangan, dalam waktu paling lama satu hari.
Sementara itu, Pasal 202 KUHAP baru menegaskan adanya kewajiban pengadilan membuka sidang pada hari yang ditetapkan, dengan konsekuensi “batal demi hukum” jika tidak dipenuhi. Yang oleh karena itu, ketidakhadiran JPU tanpa alasan sah dan tanpa pengganti jelas melanggar norma hukum yang bersifat imperative dan harus dinilai sebagai sebuah pembangkangan terhadap proses persidangan.
“Jaksa yang mangkir dari persidangan tanpa alasan sah bukan hanya sebuah kelalaian, tetapi telah mencederai integritas lembaga penegak hukum, dan harus dipandang sebagai pembangkangan terhadap proses hukum yang adil dan beradab,” sebut Wilson Lalengke.
Lulusan pasca sarjana bidang Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris, itu juga mengatakan bahwa pelangggaran hukum yang dilakukan penegak hukum akan menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap pengadilan. “Jika aparat penegak hukum sendiri melanggar hukum, bagaimana rakyat bisa percaya pada sistem peradilan? Ini adalah wajah buruk negara hukum kita. Kejaksaan harus segera menindak tegas para JPU yang absen, karena kelalaian ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan pelanggaran etik dan moral,” sebut Wilson Lalengke geram.
Pesan Filosofis untuk JPU
Kasus mangkirnya JPU dari persidangan ini dapat dibaca melalui prinsip-prinsip moralitas yang dikemukakan para pemikir besar dunia. Filsuf Yunani kuno, Plato (428–347 SM) dalam Republic menekankan bahwa keadilan adalah menempatkan setiap orang sesuai dengan perannya. Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Riau yang absen tanpa alasan sah jelas tidak menjalankan perannya; hal itu tidak saja melanggar prinsip keadilan tapi juga merupakan sebuah sikap dan perilaku amoral.
Melalui prinsip imperatif kategoris, Immanuel Kant (1724-1804) menegaskan bahwa tindakan yang memiliki nilai moral adalah perbuatan yang harus bisa dijadikan prinsip secara universal. Jika ketidakhadiran tanpa alasan sah dijadikan prinsip, maka seluruh sistem peradilan akan runtuh, yang oleh karena itu, penganut Kantianisme memandang mangkirnya JPU di persidangan sebagai hal yang tidak bermoral dan memalukan.
Lebih tegas lagi, Filsuf John Locke (1632-1794) dari Inggris menekankan tentang kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Ketika aparat hukum, dalam hal ini enam JPU dari Kejati Riau, melanggar kewajiban, maka secara otomatis kontrak sosial itu hancur, dan legitimasi negara dipertanyakan. Jika pelanggaran hukum oleh aparat hukum semacam ini terjadi secara masif dan menjadi kebiasaan, dapat dipastikan negara Indonesia akan bubar karena kontrak sosialnya telah gugur.
Untuk menanggulangi kasus JPU mangkir dari pengadilan, Montesquieu (1689-1755), mengingatkan agar kekuasaan harus diawasi dengan ketat oleh kekuasaan lain. Ketidakhadiran JPU di PN Pekanbaru Selasa kemarin menunjukkan lemahnya pengawasan internal Kejaksaan, sehingga kekuasaan aparat menjadi tirani (semena-mena) terhadap aktivis Jekson Sihombing.
Padahal, Filsuf Romawi kuno, Cicero (106-43 SM), lebih 2000 tahun lampau telah mengingatkan bahwa “Salus populi suprema lex esto” – kesejahteraan dan atau kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Ketika hukum tidak dijalankan dengan benar, kesejahteraan dan kepentingan rakyat terabaikan, itu berarti aparat yang melalaikannya telah melakukan kesalahan berat dan harus ditindak tegas.
Implikasi terhadap Hak Jekson Sihombing
Ketidakhadiran JPU di persidangan saat jadwal sidang yang telah disepakati bersama berdampak langsung pada beberapa hak Jekson Sihombing. Pertama, pengadilan melanggar hak atas peradilan cepat karena sidang harus tertunda. Kedua, hak atas kepastian hukum Jekson Sihombing terabaikan karena proses persidangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan ketiga, hak atas perlakuan adil terhadap Jekson dicederai dan menjadi korban kelalaian aparat.
“Rakyat yang diajukan ke meja hijau tidak boleh menanggung akibat dari kelalaian JPU. Karena Jekson dalam status ditahan, maka penundaan sidang adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia aktivis itu. Negara tidak boleh membiarkan hal ini terjadi,” jelas Wilson Lalengke dan meminta agar keenam JPU itu diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.
Ketidakhadiran JPU tanpa alasan sah juga berpotensi melanggar kode etik dan disiplin jaksa. Sebagai pejabat publik yang biaya hidup dan celana dalam anak-istrinya dibelikan oleh rakyat, jaksa wajib menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab. Kelalaian JPU di Riau ini menunjukkan adanya krisis integritas di tubuh Kejaksaan.
“Jaksa yang absen tanpa alasan sah harus diperiksa oleh Komisi Kejaksaan. Jika terbukti lalai, mereka harus diberi sanksi tegas. Jangan biarkan kelalaian ini menjadi budaya. Jika dibiarkan, maka keadilan akan terus dikorbankan,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
Seruan untuk Reformasi Kejaksaan
Kasus JPU mangkir dari persidangan di PN Pekanbaru itu bukanlah sebuah kasus tunggal. Perilaku jaksa yang semau-gue di berbagai daerah dalam menjalankan tugasnya merupakan fenomena umum yang amat merugikan rakyat, termasuk merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, kasus ini harus menjadi momentum untuk mereformasi Kejaksaan.
Beberapa langkah mendesak wajib diterapkan, yakni pengawasan internal harus diperkuat agar jaksa tidak bisa seenaknya mangkir atau absen dari jadwal sidang. Pengawas internal dan eksternal kejaksaan harus memberikan sanksi tegas kepada jaksa yang melanggar kewajiban. Juga, Kejaksaan Agung wajib memberlakukan sistim transparansi publik semaksimal mungkin agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya proses hukum di setiap persidangan.
“Kejaksaan tidak boleh menjadi lembaga yang tertutup dan kebal hukum. Jika jaksa melanggar, mereka harus dihukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat penegak hukum itu sendiri,” jelas Wilson Lalengke menutup pernyataannya. (TIM/Red)